KUHP Baru Berlaku Tanpa Aturan Teknis, Jaksa Bongkar 10 Pasal Rawan Kekacauan Hukum
 Ilustrasi: Viralterkini.id
Ilustrasi: Viralterkini.id Viralterkini.id, Bali – Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejak 2 Januari 2026 dipandang sebagai tonggak pembaruan hukum pidana nasional yang selama ini masih mewarisi sistem kolonial.
Reformasi tersebut bertujuan menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai sosial masyarakat.

Namun, hingga kini belum diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana KUHP baru dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan serius, mulai dari multitafsir norma hingga ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Chatarina Muliana Girsang, dalam Kuliah Umum bertema Problematika dan Poin-Poin Krusial dalam Pelaksanaan KUHP dan KUHAP 2026 di Universitas Mahasaraswati Denpasar, Senin (26/1).
“Karena memang belum ada PP sebagai aturan pelaksana KUHP baru, maka ini berpotensi menimbulkan problematika dari substansi norma dan membuka ruang multitafsir,” ujar Chatarina.
Ia mengungkapkan setidaknya terdapat 10 norma krusial dalam KUHP Nasional yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapannya.
Norma pertama adalah pengakuan terhadap hukum adat atau living law. KUHP Nasional secara eksplisit mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari asas legalitas. Namun, implementasinya membutuhkan kesiapan daerah melalui pembentukan peraturan daerah (Perda).
“Di Bali kita sudah memiliki Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2025. Tapi ini masih sangat baru dan sosialisasinya belum masif. Setiap kabupaten dan masyarakat adat punya aturan berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan dalam penegakan hukumnya,” jelasnya.
Norma kedua menyangkut pengenalan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Menurut Chatarina, pelaksanaan jenis pidana ini tidak mudah, terutama dari sisi pengawasan terhadap terpidana.
“Kami sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi banyak pelaku berasal dari luar Bali dan tinggal di kos-kosan, sehingga pengawasan menjadi sulit,” kata mantan jaksa KPK tersebut.
Ketiga, mengenai pemidanaan korporasi. KUHP Nasional secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.
Namun, pembuktiannya mensyaratkan standar yang ketat, antara lain harus dibuktikan bahwa tindak pidana merupakan keputusan kolektif direksi atau pihak berwenang serta memberikan keuntungan tidak sah bagi korporasi.
Keempat dan kelima, Chatarina menyoroti pasal-pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang berpotensi menimbulkan polemik.
Menurutnya, batas antara kritik dan penghinaan masih kabur, sementara kritik merupakan hak konstitusional warga negara.
“Makna antara mengkritisi dan dianggap menghina, baik terhadap pribadi maupun jabatannya, masih dapat menimbulkan multitafsir,” ujarnya.
Norma keenam adalah pidana mati yang kini ditempatkan sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun.
Penilaian mengenai apakah terpidana “berkelakuan baik” selama masa percobaan dinilai masih subjektif dan berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan.
Ketujuh, pengaturan delik agama dan kepercayaan, termasuk larangan memengaruhi seseorang untuk berpindah agama, juga dinilai problematik karena masuk ke ranah privat dan sulit dibuktikan secara objektif.
Kedelapan, pengaturan tentang perzinaan dan hidup bersama (kumpul kebo) yang dikualifikasikan sebagai delik aduan juga dinilai rawan menimbulkan konflik sosial.
“Ini memang masuk ranah privat, tetapi baru bisa dikriminalisasi jika ada pengaduan dari pihak tertentu,” ujarnya.
Kesembilan, norma larangan menyatakan memiliki kekuatan gaib dinilai sangat sulit pembuktiannya. Chatarina menilai pembuktian delik tersebut akan sangat kompleks karena memerlukan keterangan ahli dengan standar yang belum jelas.
“Sebagai penuntut umum, kami juga bertanya-tanya bagaimana membuktikannya,” katanya.
Kesepuluh, ketentuan mengenai aborsi yang dikecualikan bagi korban perkosaan, kekerasan seksual, atau kondisi darurat medis juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik.
Menurutnya, pembuktian status sebagai korban kekerasan seksual bukan perkara mudah.
“Kalau darurat medis jelas. Tapi kalau mengaku diperkosa, pembuktian perkosaan atau kekerasan seksual itu tidak sederhana,” ujarnya.
Selain itu, Chatarina juga menyinggung pengaturan mengenai demonstrasi yang menurutnya bukan bertujuan membatasi kebebasan berpendapat, melainkan menjaga ketertiban umum melalui mekanisme pemberitahuan kepada aparat.
“Bukan meminta izin, hanya memberitahu. Karena jika tidak diberitahukan dapat mengganggu ketertiban, seperti rekayasa lalu lintas,” katanya.
Ia menegaskan masih banyak norma dalam KUHP Nasional yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana.
Tanpa kejelasan tersebut, implementasi KUHP baru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan.
“Karena PP-nya belum ada, inilah yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasinya,” pungkas Chatarina. (**)
Pos terkait
Viral Terkini TV
IKLAN

Popular Mingguan
TIKTOK

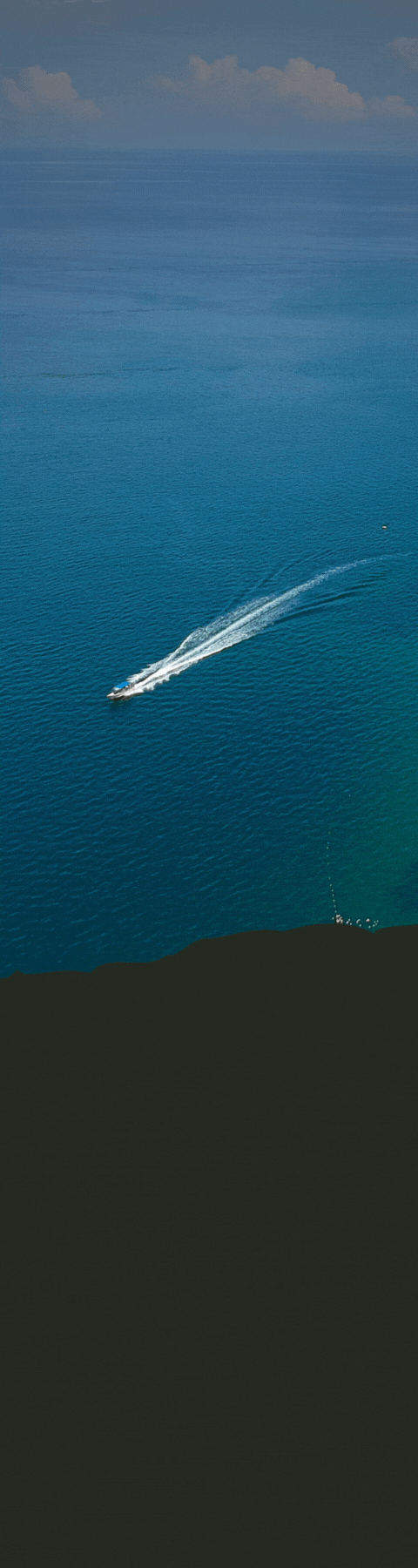
















Tidak ada komentar