Menebas Hantu Retorik, Menafasi Debat RTRW Ke Ruang Data dan Hukum

Foto: Ist.
Oleh: Hamdan Halil
Malam di sudut Kota Weda selalu punya cara untuk melambatkan waktu. Di bawah temaram lampu yang menggantung rendah, saya menyeruput ampas terakhir kopi Tawwabi racikan Yandi dengan khidmat.
Aroma pahitnya yang pekat mendadak beradu dengan “todongan” argumen dari layar gawai melalui dua tulisan Firmansyah Usman dan Sofyan Hidayat yang mencoba membedah nalar saya pada tulisan sebelumnya.
Saya menarik sebatang rokok, membiarkan asapnya membubung bersama tiap baris kalimat mereka yang saya telaah dengan senyum. Kritik mereka adalah pemantik dialektika dalam tradisi intelektual yang sehat di Maluku Utara. Terima kasih yang tulus saya ucapkan untuk itu.
Sayangnya, Saya menulis tentang Kajian Hukum Tata Ruang di Pulau Gebe tidak sedikitpun disanggah dengan kajian hukum pula. Sebuah “jawabul jawab” argumen yang saya anggap serupa nada sumbang diluar derigen kajian norma berbalut subtansi filsafati hukum. Mereka hanya membuncah untain retorika filosofis yang tampak apik dan memukau dipermukaan.
Betapapun, ada keganjilan yang menggelitik nalar; mereka berkilah di balik diksi mentereng, namun secara implisit mengayunkan belati Marx dan dekonstruksi Foucault secara serampangan di lorong hantu retorika.
Tulisan mereka mencoba memosisikan Ben Gliniecki melalui karyanya Law and Marxism sebagai striker untuk membongkar “hukum borjuasi”. Sayangnya, Gliniecki dipanggil melakukan tendangan “sunset” yang melambung jauh salah alamat.
Gliniecki memang membedah hukum dalam kerangka kelas, namun ia juga mengakui hukum sebagai medan kontradiksi yang dinamis. Menuduh Perda RTRW sebagai “milik pemodal” tanpa melihat angka pembatasan adalah bentuk anemia nalar.
Jika kita ingin menggunakan kacamata Karl Marx secara jujur, kita harus masuk ke jantung dialektika materialisme. Marx menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai superstruktur untuk mengelola krisis internal kapitalisme itu sendiri.
Dalam konteks Pulau Gebe, pembatasan zona produksi mineral sebesar 22,7 persen adalah bukti otentik upaya negara melakukan “pengereman” terhadap destruksi diri kapital agar tidak melampaui ambang batas ekologis.
Tanpa regulasi RTRW, kapitalisme akan bergerak liar tanpa sanksi legal yang mengikat, menghancurkan basis materialnya sendiri yakni alam dan tenaga kerja. Perda ini justru instrumen untuk mencegah ecological suicide.
Menuduh Perda ini murni milik pemodal menunjukkan kegagalan memahami tesis Marx tentang peran negara. Ketika ada zona konservasi yang dilarang untuk ekstraksi, itu adalah kemenangan ruang hidup atas akumulasi modal.
Untuk mempertajam anatomi hukum ini, kita perlu memanggil Roscoe Pound. Ia menegaskan hukum adalah social engineering—alat rekayasa sosial yang bertugas menyeimbangkan kepentingan yang saling bersinggungan di tengah masyarakat.
Perda RTRW bukanlah teks mati, melainkan instrumen fungsional untuk memastikan deru mesin industri tidak mematikan nadi kehidupan sosial masyarakat lokal. Menolak Perda berarti membiarkan ruang publik menjadi rimba tanpa wasit.
Lebih jauh, melalui kacamata Roberto Unger dalam Critical Legal Studies (CLS), hukum memiliki sifat indeterminacy atau kelenturan. Hukum bisa ditarik ke arah keadilan jika aktor di dalamnya mampu menggerakkan instrumen tersebut.
Di sinilah letak kekeliruan fatal mereka. Partisipasi masyarakat dan political will yang disediakan oleh regulasi dalam Pasal 71 sampai Pasal 74 Perda No. 1 Tahun 2012 adalah sebuah “celah transformatif” yang nyata.
Celah ini harus dikawal secara intelektual, bukan dibuang demi romantisme revolusi di atas kertas buram. Membuang instrumen formal atas nama perlawanan ideologis justru merupakan pengkhianatan terhadap kepentingan nyata rakyat di lapangan.
Tanpa saluran formal, rakyat akan berhadapan dengan raksasa kapital tanpa perisai legal sama sekali. Mengabaikan celah ini demi utopia adalah kemewahan berpikir yang egois karena rakyat butuh kepastian ruang, bukan sekadar teori.
Saya juga perlu mengetengahkan pemikiran Lon Fuller mengenai The Morality of Law. Fuller menekankan bahwa hukum yang valid harus memiliki kejelasan. Perda RTRW menyatukan berbagai undang-undang sektoral yang sebelumnya tumpang tindih.
Menolak logika formal adalah tindakan yang mengundang ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Tanpa struktur logika, perjuangan rakyat akan kehilangan kompas dan basis legal untuk menggugat pelanggaran wilayah di masa depan.
Sikap menyangkal realitas hukum demi romantisme utopis hanya akan merugikan posisi tawar masyarakat lokal. Ideologi tanpa instrumen hukum hanyalah orasi di pinggir jalan yang akan segera menguap ditelan perubahan zaman.
Perda RTRW adalah jembatan menuju kesejahteraan yang terukur dan instrumen holistik yang memastikan pembangunan tidak menggilas martabat kemanusiaan. Rakyat butuh kepastian ruang untuk bernapas, bekerja, dan hidup terhormat.
Marilah kita berhenti menjadi “pemanggil hantu” dan mulailah menjadi pembelajar hukum yang jujur dan integral. Jika dialektika ini ingin berlanjut, bawalah data dan kajian hukum yang mumpuni ke meja diskusi secara dewasa.
Jangan lagi menyajikan hidangan retorika yang menderita anemia nalar di hadapan publik yang kian cerdas. Dalam tradisi intelektual sejati, pisau analisis digunakan untuk membedah fakta, bukan menebas kebenaran demi ego semata.
Penulis adalah Koordinator Pemerhati Kelola Sumber Daya Alam (PKSDA)

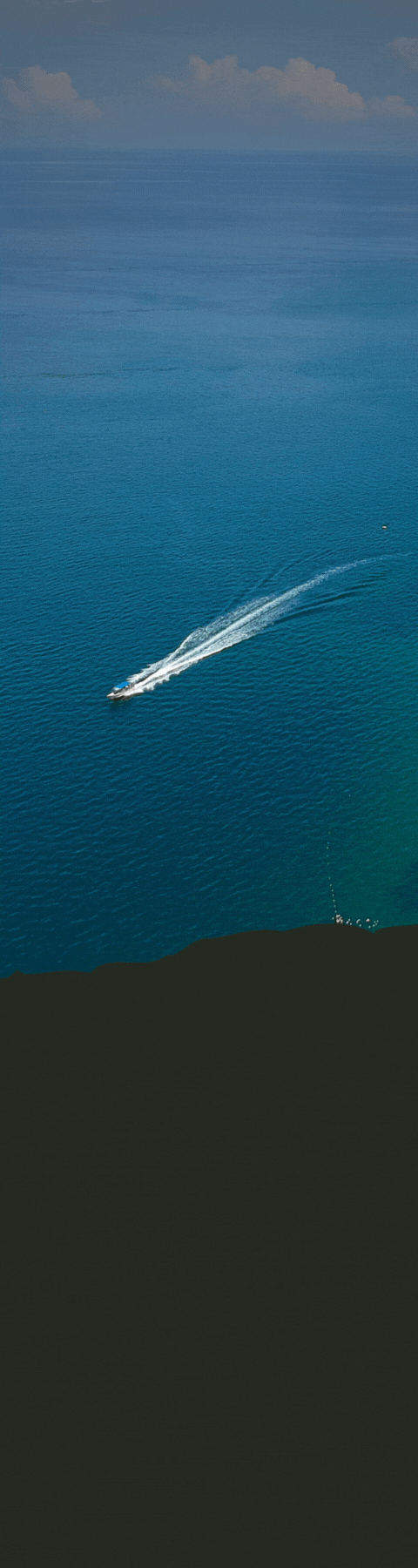

















Tidak ada komentar