Anemia Nalar dalam Debat Tata Ruang: Siapa yang Sebenarnya Membela Rakyat?
 Foto: Ist
Foto: Ist Oleh: Hamdan Halil
MEMBACA ARTIKEL saudara Bung Firmansyah Usman bertajuk “Ketika Simfoni Tata Ruang Menjadi Alibi Kekuasaan”, yang dialamatkan untuk menguliti tulisan saya sebelumnya, saya sejenak terhenti. Sambil menyeruput kopi khas Tawwabi racikan Yandi di depan gereja Kota Weda, saya menelaah setiap barisnya dengan rasa kagum.
Saya kembali menyeruput kopi itu sembari menarik sebatang rokok penuh nikmat, membiarkan kepulan asapnya membungkus pikiran yang kian jernih. Meskipun Bung Firmansyah mencoba menelanjangi keberpihakan saya, saya memuliakan dialektika ini sebagai fragmen pendewasaan berpikir di kerasnya aspal jalanan.
Namun, keberpihakan itu bukanlah ruang hampa makna yang lahir dari sekadar retorika belaka. Ia adalah pilihan sadar untuk membaca realitas melalui instrumen perjuangan yang mumpuni, di tengah upaya kita menata karut-marut pengelolaan sumber daya alam yang selama ini memunggungi nasib rakyat.
Narasi Bung Firmansyah Usman justru menyingkap sebuah pemandangan logika yang memprihatinkan; sebuah kondisi yang saya sebut sebagai Anemia Nalar. Penulisnya terjebak dalam kebiasaan buruk membaca hukum dengan prasangka, sebuah kecenderungan yang melalaikan aturan demi kecurigaan subjektif.
Gejala ini melahirkan Nalar Tabolabale, sebuah upaya jungkir balik yang mencoba mengganti kedaulatan regulasi dengan mitos alibi kekuasaan. Kegagalan epistemologis ini terlihat saat Bung Firmansyah meminjam jubah Karl Marx hingga Michel Foucault secara serampangan untuk melegitimasi sentimen personalnya.
Dalam totalitas pandangan Karl Marx, kekuatan produksi adalah motor pembebasan manusia. Bung Firmansyah keliru jika memandang tata ruang hanya sebagai alat borjuasi; sebab tanpa penataan ruang produksi, rakyat justru terjebak dalam alienasi dan kemiskinan permanen yang menindas martabat mereka.
Marx mengajarkan bahwa basis ekonomi menentukan superstruktur hukum. Tata ruang yang saya bela adalah ikhtiar untuk mengubah basis materi tersebut agar rakyat Gebe tidak lagi menjadi sekadar penonton di tanah sendiri, melainkan subjek yang memegang kendali atas alat-alat produksinya secara sah.
Bung Firmansyah juga tampak gagap saat menyeret Michel Foucault ke dalam gelanggang. Ia menggunakan konsep “kuasa” secara dangkal, seolah setiap regulasi adalah opresi. Padahal, bagi Foucault, kuasa bersifat kapiler dan produktif; ia tidak hanya menindas, tetapi juga menata dan memajukan kehidupan.
Tata ruang dalam perspektif Foucault adalah bentuk Governmentality yang positif. Ia merupakan instrumen biopolitik untuk mengelola populasi agar terhindar dari anarki ruang. Menolak tata ruang dengan alibi “anti-kekuasaan” justru akan menjerumuskan rakyat ke dalam kekosongan hukum yang mematikan.
Di titik ini, Bung Firmansyah tampak mengekor pada kegelisahan Hannah Arendt yang keliru menilai Martin Heidegger. Arendt mungkin benar dalam ruang lingkup vita activa, namun ia gagal memahami kedalaman Heidegger yang melihat manusia bukan sekadar alat politik, melainkan sebagai Dasein yang meruang.
Bung Firmansyah keliru menilai Heidegger dengan prasangka Arendtian. Menolak otoritas hukum demi romantisme kebebasan abstrak hanya akan membiarkan Kapitalisme predatorik melumat ekologi kita. Tata ruang hadir justru untuk mendisiplinkan kapital agar tunduk pada norma publik dalam filsafat Hans Kelsen.
Keberlanjutan sejati harus berdiri di atas pilar ekonomi, sosial, dan ekologi secara seimbang. Mengutip Mansour Fakih, pembangunan bukanlah seteru rakyat selama ia mampu meniti jalan tengah. Tata ruang adalah bejana transformasi agar kekayaan alam Gebe dikelola dengan nalar yang jernih dan bertanggung jawab.
Membaca hukum dengan prasangka hanya akan melahirkan kebencian kolektif, bukan solusi jangka panjang. Perjuangan hukum menuntut pembuktian legal standing di Mahkamah Agung melalui parameter yang rigid, bukan sekadar membangun narasi kecurigaan di atas pasir hisap retorika jalanan yang tidak terukur.
Bersuara lantang tanpa menawarkan jalur Judicial Review hanyalah bentuk “gagah-gagahan” intelektual yang menyembunyikan ketidaksiapan berdebat di palung substansi. Menolak kebijakan tanpa alternatif naskah akademik tandingan adalah bentuk sabotase intelektual yang tidak bertanggung jawab pada masa depan daerah.
Kita harus jujur mengajukan pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang berpihak kepada rakyat? Apakah Bung Firmansyah yang terjebak dalam romantisme emosional, atau mereka yang memilih realisme konstitusional demi menjamin hak rakyat untuk “berada” secara bermartabat di tanah kelahirannya?
Tata ruang adalah janji kedaulatan hukum untuk masa depan Gebe. Di atas kedaulatan itulah kita harus berdiri tegak, bukan di atas prasangka yang indah dalam kata namun kosong dalam tindakan nyata bagi kesejahteraan rakyat yang selama ini merindukan kepastian hidup dan kemajuan peradaban. (**)
*) Penulis adalah Koordinator Pemerhati Kelola Sumber Daya Alam (PKSDA)

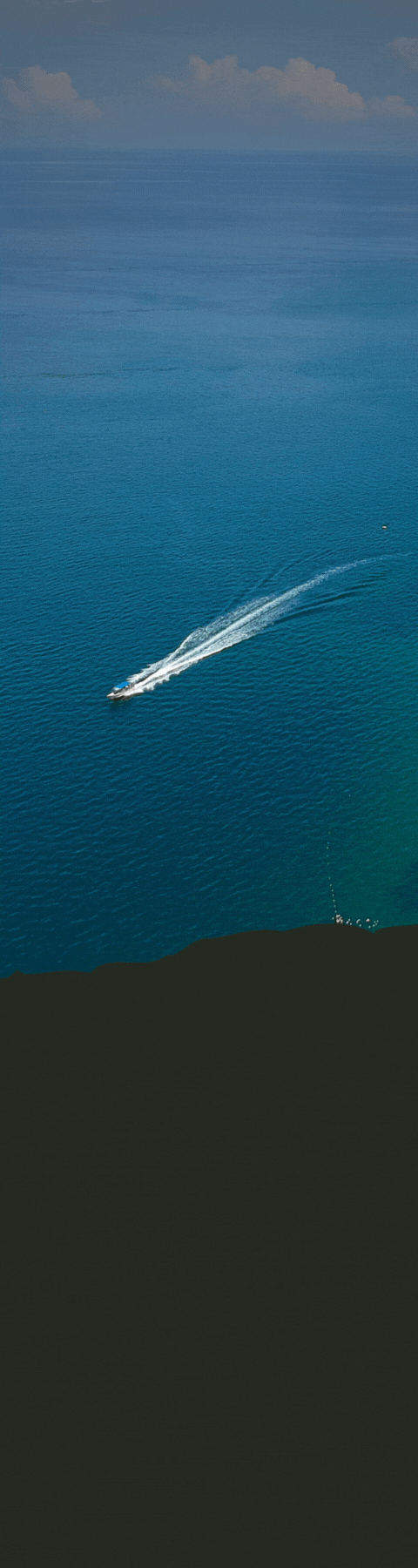


















Tidak ada komentar