Dugaan Pelecehan Seksual Thanksinsomnia Viral, Ini Alasan Psikologis Korban Sulit Melapor
 Ilustrasi: Viralterkini.id
Ilustrasi: Viralterkini.id Viralterkini.id – Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Mohan Hazian, pemilik label busana Thanksinsomnia, kembali menyita perhatian publik setelah unggahan akun @aarummanis di platform X menjadi viral.
Dalam pengakuannya, korban mengungkap pengalaman traumatis yang dialaminya seusai sesi pemotretan pada Mei 2025.
Awalnya, kegiatan profesional tersebut berjalan normal. Namun situasi berubah ketika Mohan diduga mengajak korban makan bersama dan kemudian melakukan sejumlah tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual.
Pengakuan ini tidak berhenti pada satu cerita. Seiring waktu, muncul dugaan bahwa korban bukan hanya satu orang.
Cerita yang beredar di media sosial memicu reaksi luas dan membuka kemungkinan adanya pola perilaku serupa yang dialami pihak lain.
Respons keras datang dari mitra kerja Mohan. Shira Media, sebagai penerbit bukunya, menyatakan menghentikan seluruh kerja sama komersial serta membatalkan rencana cetak ulang sejak Selasa, (10/2/2026).
Sementara itu, manajemen Thanksinsomnia menyampaikan bahwa Mohan telah dinonaktifkan dari seluruh kegiatan operasional perusahaan sejak 9 Februari 2026.
Pihak perusahaan menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan pribadi. Di sisi lain, Mohan membantah seluruh tuduhan melalui video klarifikasi di Instagram dan menyatakan dirinya dirugikan secara pribadi maupun profesional.
Munculnya laporan yang baru disampaikan jauh setelah peristiwa terjadi kerap memancing keraguan sebagian masyarakat.
Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa korban memilih diam begitu lama dan baru bersuara sekarang.
Padahal, realitas psikologis korban jauh lebih kompleks dari sekadar keberanian untuk berbicara.
Trauma yang Membungkam Suara Korban
Keterlambatan pelaporan sering kali berujung pada praktik menyalahkan korban (victim blaming). Padahal, data dari Equal Employment Opportunity Commission mencatat sekitar 12.000 laporan pelecehan seksual berbasis gender setiap tahun, dengan mayoritas pelapor adalah perempuan.
Namun angka tersebut diyakini hanya mewakili sebagian kecil dari kejadian yang sebenarnya.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tiga dari empat penyintas pelecehan seksual tidak pernah melaporkan peristiwa yang mereka alami kepada pihak berwenang.
Banyak dari mereka memilih menghindari pelaku, meremehkan kejadian, atau berusaha menghapusnya dari ingatan.
Hambatan utama untuk bersuara adalah rasa malu yang mendalam. Psikolog Gershen Kaufman dalam bukunya Shame: The Power of Caring menjelaskan bahwa rasa malu muncul ketika martabat dan integritas diri seseorang dilanggar.
Pelecehan seksual membuat korban merasa hina, tidak berdaya, dan akhirnya menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi.
Fenomena ini terlihat dalam berbagai kasus global, termasuk pengakuan Lee Corfman yang melaporkan Roy Moore atas pelecehan saat dirinya masih berusia 14 tahun.
Ia sempat merasa bahwa kejadian tersebut adalah kesalahannya sendiri.
Rasa malu sering kali diperkuat dengan mekanisme pertahanan diri berupa penyangkalan.
Banyak korban meyakinkan diri bahwa apa yang mereka alami “tidak separah” kasus kekerasan seksual lain, sehingga dianggap tidak layak dilaporkan.
Padahal dampaknya tetap serius. Di balik tampilan luar yang tampak baik-baik saja, banyak penyintas mengalami depresi, kehilangan kepercayaan diri, hingga menarik diri dari lingkungan sosial.
Berbagai penelitian menunjukkan kaitan erat antara pelecehan seksual dengan risiko gangguan stres pascatrauma (PTSD) dan kecenderungan bunuh diri.
Secara statistik, sekitar 15 dari setiap 1.000 perempuan yang mengalami pelecehan pernah mencoba mengakhiri hidupnya.
Selain tekanan batin, ketakutan terhadap konsekuensi sosial juga menjadi penghalang besar. Korban kerap khawatir kehilangan pekerjaan, dicap sebagai pembuat masalah, atau dihancurkan reputasinya.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, terutama ketika pelaku memiliki kekuasaan atau pengaruh besar, seperti yang terlihat dalam kasus Harvey Weinstein di industri film.
Ketakutan tersebut diperparah oleh kondisi psikologis yang dikenal sebagai learned helplessness, yakni perasaan tidak berdaya yang membuat seseorang percaya bahwa apa pun yang dilakukan tidak akan mengubah keadaan.
Budaya yang masih memandang perempuan sebagai objek seksual juga memperparah situasi.
Dr. Laurel Watson dari University of Missouri–Kansas City menyebut objektifikasi seksual sebagai bentuk “teror psikologis” yang menumbuhkan rasa takut dan kecemasan akan kekerasan fisik sejak usia dini.
Bagi korban yang memiliki riwayat trauma masa kecil, kecenderungan untuk diam semakin besar. Data menunjukkan sekitar 38 persen mahasiswi korban kekerasan seksual pernah mengalami kejadian serupa sebelum memasuki perguruan tinggi.
Trauma berulang ini sering memicu reaksi “membeku” (freezing response) saat menghadapi ancaman, yang kerap disalahartikan sebagai persetujuan.
Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami gangguan ingatan akibat pengaruh alkohol atau obat-obatan yang digunakan pelaku, seperti yang terungkap dalam perkara Bill Cosby.
Disosiasi saat trauma terjadi dapat membuat memori menjadi terpecah dan sulit diungkapkan secara utuh.
Sering kali, dibutuhkan satu suara pertama yang berani berbicara agar korban lain merasa cukup aman untuk mengakui pengalaman mereka sendiri.
Memahami kompleksitas psikologis ini seharusnya menggeser arah perdebatan publik.
Pertanyaan penting bukan lagi mengapa korban baru melapor sekarang, melainkan mengapa budaya pelecehan masih terus terjadi dan bagaimana masyarakat dapat menciptakan ruang yang aman bagi para penyintas untuk memperoleh keadilan. (**)

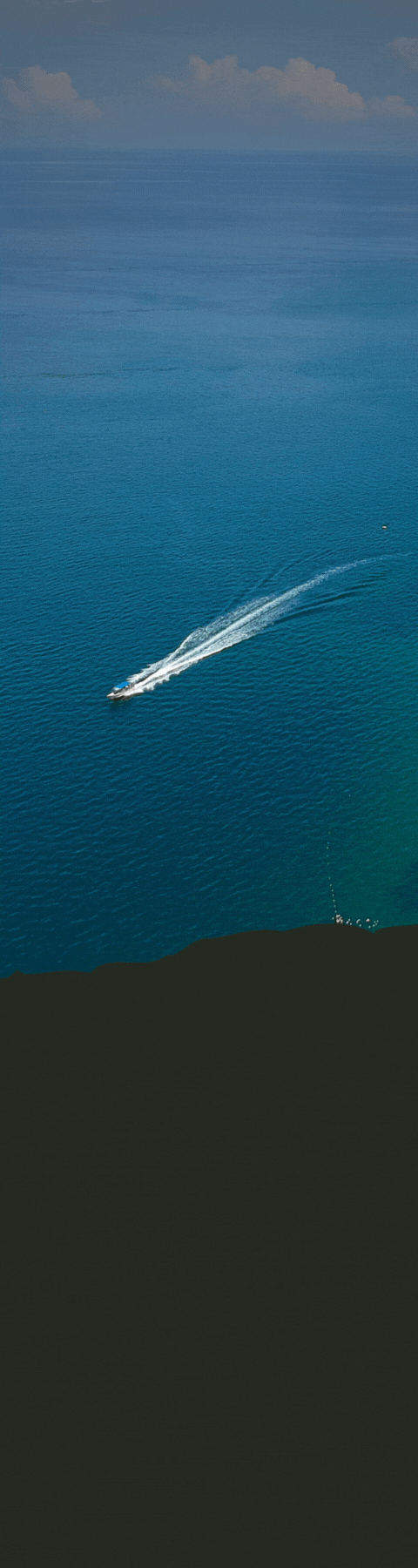

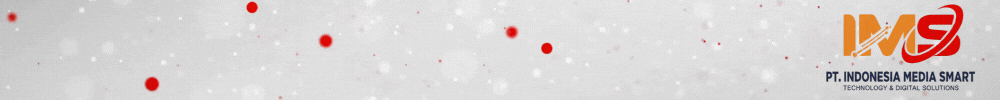


















Tidak ada komentar