Putus Asa di Usia Sekolah: Kegagalan Negara Melindungi Kesehatan Mental Anak

KEMATIAN SEORANG ANAK sekolah dasar yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli pena dan buku bukan hanya tragedi sosial, tetapi juga bukti kegagalan negara dalam melindungi kesehatan mental anak. Peristiwa ini tidak dapat dipahami secara dangkal sebagai persoalan ekonomi semata, melainkan harus dibaca melalui lensa psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi kebijakan publik.
Dalam teori psikososial Erik Erikson (1968), anak usia sekolah dasar berada pada tahap industry versus inferiority, yaitu fase ketika anak membangun rasa mampu, percaya diri, dan kompetensi melalui keberhasilan belajar dan pengakuan sosial. Ketika anak berulang kali mengalami kegagalan atau merasa gagal karena tidak mampu memenuhi tuntutan sekolah maka yang tumbuh bukanlah rasa percaya diri, melainkan perasaan rendah diri dan tidak berharga.
Dalam konteks ini, ketidakmampuan membeli pena dan buku tidak dipersepsikan anak sebagai masalah struktural, melainkan sebagai cacat diri. Dengan kata lain, anak tersebut tidak mati karena ketiadaan alat tulis, tetapi karena runtuhnya harga diri dan harapan hidup. Ini adalah sinyal bahwa sistem pendidikan dan perlindungan sosial telah gagal menyediakan lingkungan psikologis yang aman bagi anak-anak miskin.
Dari perspektif psikologi sosial, kemiskinan adalah pengalaman psikologis yang kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan pada anak berkaitan erat dengan meningkatnya stres kronis, kecemasan, dan risiko depresi (APA, 2017). Anak-anak dari keluarga miskin sering kali mengalami toxic stress, yaitu tekanan psikologis berkepanjangan tanpa dukungan emosional yang memadai. Tekanan inilah yang dapat mengganggu perkembangan emosi dan kemampuan anak dalam mengatasi masalah.
Sekolah, yang seharusnya menjadi ruang pemulihan dan perlindungan, justru sering kali memperkuat tekanan tersebut. Teguran guru, tuntutan akademik tanpa empati, atau perlakuan berbeda karena keterbatasan ekonomi dapat memperdalam rasa malu dan keterasingan. Dalam teori labeling dalam psikologi sosial, stigma yang dilekatkan baik secara eksplisit maupun implisit dapat membentuk identitas negatif pada anak. Anak mulai percaya bahwa dirinya memang “tidak mampu” dan “tidak layak”.
Lebih jauh, tragedi ini dapat dijelaskan melalui model ekologi perkembangan manusia dari Urie Bronfenbrenner dalam bukunya The Ecology of Human Development (1979).Dalam model ini, perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai sistem yang saling berinteraksi: keluarga, sekolah, kebijakan negara, hingga budaya.
Ketika negara gagal memastikan akses pendidikan dasar yang bermartabat, maka kegagalan tersebut merembes hingga ke ruang kelas dan akhirnya menghantam psikologis anak. Bunuh diri anak bukan peristiwa individual, melainkan hasil interaksi sistem yang gagal bekerja.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa kesehatan mental anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak anak. WHO juga mencatat bahwa gangguan kesehatan mental dapat muncul sejak usia dini, dan intervensi awal di lingkungan sekolah sangat menentukan pencegahan risiko bunuh diri di kemudian hari.
Namun realitas di Indonesia menunjukkan bahwa layanan kesehatan mental di sekolah dasar masih sangat terbatas, baik dari sisi kebijakan maupun sumber daya manusia. Guru kelas, yang setiap hari berinteraksi langsung dengan anak, sering kali tidak dibekali pelatihan psikologi perkembangan dan kesehatan mental dasar.
Padahal, menurut UNICEF, guru memiliki peran strategis dalam deteksi dini tanda-tanda distress psikologis pada anak, seperti penarikan diri sosial, perubahan perilaku ekstrem, atau ekspresi keputusasaan. Tanpa pelatihan dan sistem pendukung, tanda-tanda ini mudah diabaikan hingga berujung pada tragedi.
Dari sudut pandang psikologi krisis, bunuh diri pada anak hampir selalu merupakan hasil akumulasi tekanan psikologis, bukan satu kejadian tunggal. Artinya, tragedi ini sangat mungkin dicegah jika negara memiliki sistem perlindungan yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Kegagalan mencegahnya menunjukkan bahwa kesehatan mental anak belum menjadi prioritas kebijakan publik.
Pemerintah sering kali merespons tragedi semacam ini dengan belasungkawa dan janji evaluasi. Namun dalam psikologi moral, empati yang tidak disertai tindakan struktural disebut sebagai moral licensing atau perasaan telah “berbuat baik” tanpa perubahan nyata. Negara perlu bergerak melampaui simpati simbolik menuju kebijakan berbasis bukti psikologis.
Ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, pendidikan dasar harus dipahami sebagai intervensi psikologis preventif. Menjamin ketersediaan alat tulis dan kebutuhan belajar bukan hanya soal akses pendidikan, tetapi perlindungan terhadap harga diri dan kesehatan mental anak. Penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar dapat menurunkan stres dan meningkatkan rasa aman psikologis pada anak.
Kedua, pelatihan guru berbasis psikologi perkembangan dan pendekatan empatik harus menjadi kebijakan nasional. Guru bukan sekadar pengajar kurikulum, tetapi significant others yang sangat memengaruhi konsep diri anak. Dalam banyak kasus, satu kalimat dari guru dapat menjadi sumber harapan atau sebaliknya, menjadi sumber luka psikologis jangka panjang.
Dan ketiga, layanan konseling sekolah harus diperluas hingga jenjang pendidikan dasar. Menganggap konseling hanya relevan untuk remaja adalah kesalahan besar. Anak-anak juga mengalami kecemasan, rasa bersalah, dan keputusasaan, hanya saja mereka belum memiliki bahasa yang cukup untuk mengekspresikannya.
Tragedi ini juga menuntut refleksi kolektif masyarakat. Dalam psikologi budaya, normalisasi penderitaan anak miskin merupakan bentuk kekerasan simbolik. Ketika kita menyebut tragedi ini sebagai “takdir” atau “kejadian langka”, kita sedang mengabaikan realitas psikologis yang dialami ribuan anak lain dalam diam.
Negara harus sadar bahwa anak-anak tidak memiliki kapasitas psikologis untuk menanggung kegagalan sistem. Ketika seorang anak merasa kematiannya lebih masuk akal daripada hidup tanpa pena dan buku, maka yang runtuh bukan hanya hidup seorang anak, tetapi rasa aman psikologis sebuah bangsa.
Ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada angka dan indeks. Ia harus diukur dari sejauh mana negara mampu menjaga harapan, harga diri, dan kesehatan mental anak-anaknya. Satu anak yang mati karena tekanan kemiskinan adalah satu kegagalan besar yang tidak boleh terulang.
Ketika pena dan buku menjadi alasan kematian, maka yang sesungguhnya sedang hancur adalah komitmen kita terhadap kemanusiaan dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Negara harus hadir sebagai pelindung jiwa, bukan sekadar pengelola anggaran.
Tidak boleh ada lagi anak yang merasa hidupnya tidak berharga hanya karena miskin. Jika tragedi ini tidak menjadi titik balik kebijakan berbasis psikologi dan keadilan sosial, maka kita sedang membiarkan luka yang sama terus diwariskan. Semoga menjadi pembelajaran bersama!
*) Penulis adalah Dosen UMMU Ternate dan Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Maluku Utara.

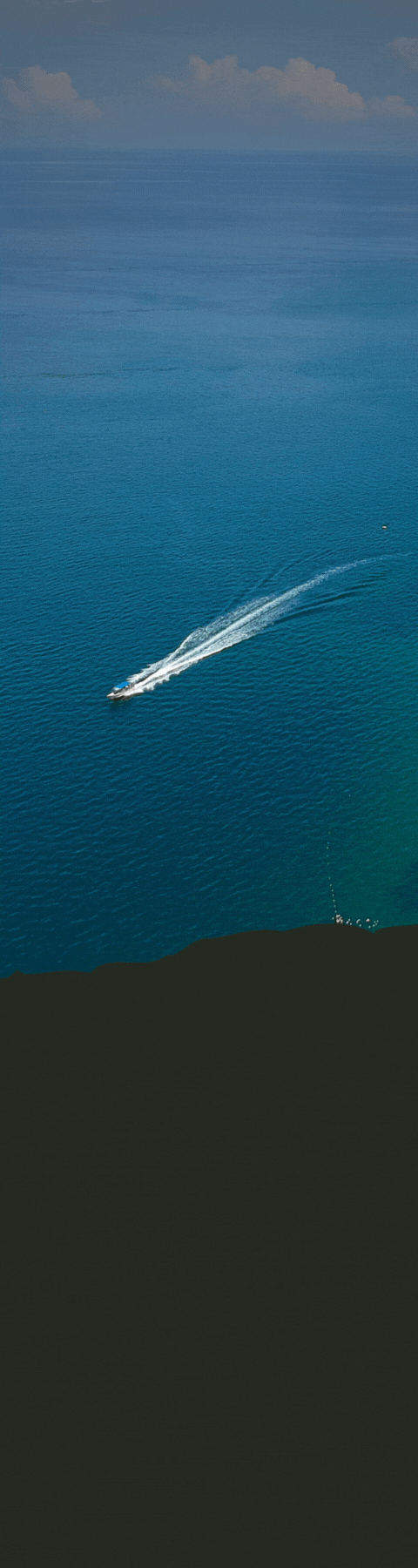


















Tidak ada komentar